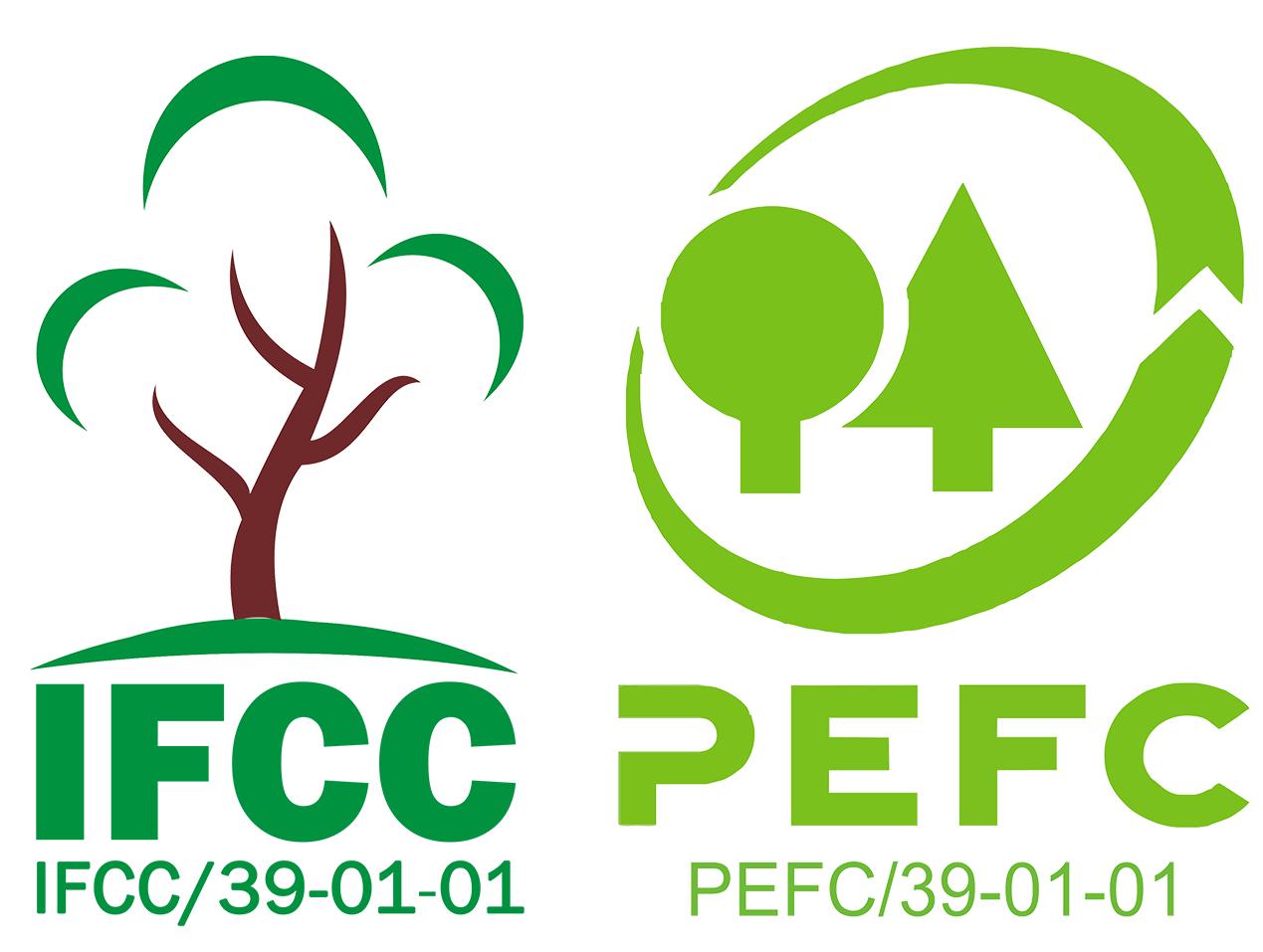Oleh Nurcahyo Adi
Pernah nonton film komedi Flintstone? Film yang dibintangi antara lain oleh John Goodman tesebut adalah film komedi yang menceritakan kehidupan manusia jaman batu. Di dalamnya digambarkan orang-orang yang masih menggunakan pakaian alami yang belum banyak diolah, dari kulit hewan dan kulit kayu.
Ketika melihat berbagai buku cerita dan gambar tentang orang jaman dulu, atau film tentang manusia purba, sering digambarkan bahwa manusia jaman dulu itu mengenakan baju/pakaian dari bahan alami, antara lain dari kulit kayu. Pakaiannya digambarkan secara fisik mirip dengan kulit kayu, terlihat masih kaku, asli, tampak serat dan gambar kayunya, serta sangat mudah dikenali bahwa bahan penutup badan tersebut berasal dari kulit kayu.
Dalam perkembangannya, ketika manusia berubah lebih maju dan mempunyai pengetahuan untuk mengenali serat kain dari bahan lainnya, penutup badan dari kayu mulai ditinggalkan. Kain pembuat pakaian kemudian banyak dibuat dari serat kapas atau katun, dan belakangan banyak dibuat dari serat sintetis dan bahan lainnya melalui proses inovasi teknologi yang mutakhir.
Dalam tahun-tahun belakangan, beberapa organisasi mulai melakukan penelitian dan pengembangan bahan baku yang lebih sustainable (renewable) dan lebih ramah lingkungan sebagai bahan pembuat kain dari kayu/pohon. Hutan dengan pohon-pohonnya dilirik kembali oleh sektor industri ini sebagai sumber renewable material untuk pembuatan kain, yang digunakan tidak hanya dari kulitnya, tapi juga diekstrak dari serat kayu yang terkandung di dalam pohon. Berbagai upaya promosi juga sudah dilakukan oleh berbagai lembaga dan negara di dunia untuk membuat kain dari kayu/pohon tersebut.
Pada acara pertemuan PEFC (sebuah lembaga nir laba yang mempromosikan kelestarian lingkungan/hutan berkantor pusat di Geneva, Swiss), setiap tahunnya selalu terdapat sesi sharing berbagai inovasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing negara.
Tahun ini, wakil dari Italy menampilkan kain dan pakaian jadi ramah lingkungan yang terbuat dari serat kayu. Serat-serat kayu tersebut dipromosikan berasal dari pohon dalam hutan yang telah bersertifikat dikelola secara lestari. Berbagai merek dunia yang terkenal sudah menggunakan kain yang berbahan dari kayu tersebut. Tidak saja berbentuk kain, tetapi juga yang sudah diolah lebih lanjut menjadi kaos, T-shirt, jaket, celana panjang dan lain-lain.
Baju/pakaian tersebut kemudian dikategorikan dalam kelompok yang disebut sebagai sustainable fashion.
Di Indonesia, juga terdapat sedikitnya sebuah perusahaan yang dalam lima tahun terakhir ini juga sudah mulai melirik kesempatan ini dengan memproduksi kain ramah lingkungan dari bahan kayu tropis yang dapat ditanam kembali (renewable). Melihat potensi pasar yang cukup besar di Indonesia dan dunia, tidak tertutup kemungkinan perusahaan tersebut akan segera mengembangkan produk kain/pakaian ramah lingkungannya menyaingi produk dari negara maju. Tentu saja apabila tidak terdapat hambatan non teknis, seperti hambatan investasi, perang dagang, persaingan pasar dengan negara industri besar, dan lain-lain, yang biasanya malahan lebih memakan energi dalam menyelesaikan persoalannya.
Dalam kaitannya dengan sustainable fashion ini, berbagai referensi menyebutkan bahwa emisi karbon dari industri garment cukup tinggi. Untuk membuat sebuah T-shirt berbahan baku katun, dibutuhkan sekitar 2.700 liter air. Ini sama dengan 140 galon besar air mineral, atau kebutuhan air PDAM rata-rata sebuah keluarga menengah di Bogor selama 3 hari.
Daftar kebutuhan airnya bisa lebih panjang lagi apabila kita akan membuat daftar semua produk tekstil dan produk turunannya.
Oleh karena itu, industri garmen dipandang sebagai sebuah industri yang boros air. Atas alasan itu beberapa penelitian dilakukan untuk mencari alternatif bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi.
Penggunaan kayu sebagai bahan baku pembuatan kain dipandang memenuhi kriteria tersebut.
Industri harus sudah semakin menyadari bahwa ketersediaan air itu tidak sesederhana memutar kran. “A single drop of water in the uplands of a watershed is likely the same drop of water may appear in consideration of climate and microclimate, flood, water supply, forestry, industry commerce, scenic beauty etc” (Ian McHarg, yang dianggap sebagai kakek Ecological Design dalam menjelaskan siklus air, 1995).
Spinnova sebuah perusahaan (sustainable fibre company) dari Finlandia menyebutkan bahwa bahan baku serat kayu menghemat penggunaan air hampir 99% dan menggunakan energi 80% lebih hemat. Stora Enso, sebuah perusahaan yang memproduksi pulp, kertas dan produk kayu lainnya dari Finland menyatakan bahwa keuntungan dari kain berbahan baku serat kayu adalah:
1. Renewable resource --- sumber bahan baku yang bisa diperbaharui. Sementara polyester yang merupakan bahan baku lainnya untuk membuat kain, turunan dari produk yang dihasilkan dari fosil, tidak dapat diperbaharui.
2. Production benefits: membutuhkan air yang lebih sedikit dibandingkan dengan katun, lebih sustainable dari pada polyester, membutuhkan lahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan wool.
3. Konten cellulose tinggi, high brightness level, and molecular-weight distribution.
4. Lebih mudah bercampur dengan bahan serat lainnya.
5. Lebih soft, natural dan warna yang lebih tahan lama.
Saat ini suplai produk kain dan turunannya sebagian besar masih berasal dari yang berbahan baku polyester (55%) dan katun (27%). Sementara dari bahan selulosa kayu baru sekitar 6%. Sisanya berasal dari Wool dan bahan sintetis Polypropylen dan Acrilic. Melihat komposisi bahan baku sebagian besar dari sumber yang tidak renewable dan cenderung tidak ramah lingkungan, maka tuntutan pada sektor industri tekstil dan fashion juga semakin meningkat untuk melakukan praktek-praktek yang lebih bertanggung jawab dengan merubah bahan baku yang lebih ramah lingkungan.
Menurut Spinnova, hutan di Finland sendiri dapat memproduksi kain dari serat kayu lebih kurang sama dengan kemampuan seluruh dunia memproduksi kain dari katun. Oleh karena itu penggunaan serat kayu sebagai bahan baku kain merupakan revolusi industri tekstil dan sekaligus revolusi industri kehutanan.
Dari sisi pasar, perilaku konsumen untuk lebih hijau, mempunyai alternatif untuk memilih bahan baku kain yang berasal dari renewable resources. Pilihan ini adalah yang terkait dengan proses produksi yang dilakukan oleh produsen. Dalam rantai pasokan, konsumen berhak untuk mengetahui asal usul bahan baku yang renewable dan sustainable. Tidak bisa lagi dikatakan seperti pepatah lama, “What they don’t know, can’t hurt them”.
Akibat dari proses produksi dan industrialisasi yang masif, efek negatif yang melukai terhadap socio-environment sudah bisa dirasakan oleh masyarakat.
Konsep sustainable itu sendiri sebenarnya bisa dikelompokkan lagi berdasarkan upaya aktif yang bisa kita lakukan. Hal itu sejalan dengan kecenderungan yang ditengarai Mc Lennan, bahwa masyarakat saat ini sudah aktif menuju pada gerakan kesadaran lingkungan yang lebih maju.
Selain mengetahui asal usul bahan baku, masyarakat/konsumen kain dapat berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan dengan melakukan tiga hal atau 3R, yaitu reduce, reuse dan recycle (mengurangi, menggunakan kembali dan melakukan daur ulang), atas suatu produk atau barang, yang tujuan akhirnya adalah mengurangi beban atau tekanan atas penggunaan sumber daya alam, yang digunakan yang semakin hari semakin terbatas. Itulah yang disebut Daniel Goleman sebagai “mindfully ecological intelligence shoppers”.
Amsterdam mengklaim diri sebagai salah satu kota fashion dunia. Berbagai model pakaian dengan berbagai merek terkenal dunia bisa dijumpai di Amsterdam. Dalam kaitannya dengan kesadaran mengurangi carbon footprint, dia mempromosikan bahwa Amsterdam adalah kota dengan paling banyak toko yang menjual pakain reuse (pakaian yang bisa digunakan lagi) di daratan Eropa. Berbagai toko pakaian bekas dari merek terkenal dunia bisa dijumpai di Amsterdam. Bahkan bulan April 2019 ini mereka menggelar IJ-Hallen Market, semacam flea market atau pasar loak terbesar dengan 750 stand barang/pakain bekas.
Dengan kondisi seperti itu, masyarakat Amsterdam bisa menyatakan diri sebagai masyarakat yang berpartisipasi mengurangi emisi karbon. Apabila jumlah pakaian bekas yang dijual kemudian dikalkulasi dan dikaitkan dengan pengurangan penggunaan air, maka itulah kontribusi masyarakat Amsterdam terhadap lingkungan, khususnya terhadap pengurangan emisi karbon.
Bagaimana dengan kita? Saya baru ngeh …… dalam konteks berpakaian, banyak masyarakat kita yang sebenarnya sudah mempraktekkan kesadaran lingkungan dengan memakai pakaian yang sebenarnya masuk kategori eco-friendly. Reduce (mengurangi beli baju) sudah pasti, karena makan nasi Padang lebih prioritas, kecuali lebaran. Reuse (menggunakan pakaian bekas pakai orang lain) sering dilakukan karena lebih murah dan mudah diperoleh dimana-mana, dekat emper stasiun dan terminalpun ada. Disamping itu, masyarakat Indonesia juga suka sekali memberi kesempatan orang lain untuk berperilaku ramah lingkungan juga, dengan menjual atau memberikan baju bekas pakainya.
Apalagi kalau kita bisa kalkulasi juga, berton-ton pakaian bekas yang masuk ke Indonesia beberapa tahun yang lalu. Pakaian reuse itu ….. entah dari mana asalnya, bisa kita temui di seluruh pelosok Indonesia saat itu, yang kemudian mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat Indonesia.
JIka beribu ton pakaian reuse itu bisa kita klaim sebagai kontribusi Indonesia dalam mereduksi penggunaan air, yang bisa jadi berjuta-juta ton m3 dan mengurangi carbon-footprint …… kita tidak perlu repot-repot mikirin Paris Agreement yang memaksa kita menghentikan berbagai kegiatan eksploratif kita, untuk mengurangi peningkatan suhu bumi.
Kalau Amsterdam berani klaim dan recognised (paling tidak secara komersial supaya flea-merketnya laku), seharusnya masyarakat Indonesia direkognisi dunia juga. Itulah fairness, kalau kita mau mengesampingkan azas inequality. Equality is working when there is inequality (anonim).
Atau ini dorongan atau inspirasi buat kita untuk lebih kreatif dalam melakukan environment-political claim di tataran dunia. Jangan-jangan kita akan dapat juara sebagai the most Sustainable fashion country.
Geneva, 9 April 2019